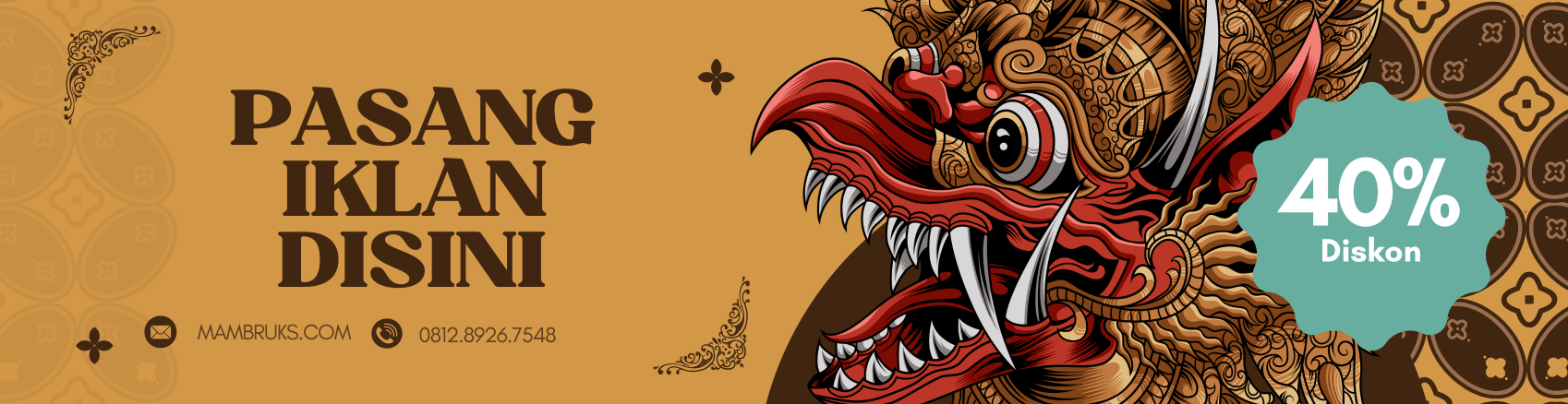Jakarta, Mambruks.Com-Perempuan Adat Papua mencurahkan isi hatinya pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Khusus perayaan tahun ini, Perempuan Adat Papua berbicara dalam forum bertajuk ‘Sa Pu Kisah’ menuturkan harapan dan kenyataan yang mereka alami tentang rusaknya alam Papua dan ancaman terhadap kehidupan yang berkelanjutan di tanah Papua.
Pendeta Magdalena Kafiar dari Bidang Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau KPKC Sinode mengatakan, praktik pengetahuan tradisional dan pemanfaatan hutan berkelanjutan salah satunya dilakukan oleh perempuan adat di Tanah Papua. Sebagai contoh aksesoris dan ramuan obat-obatan yang bahannya berasal dari hutan.
Namun kata dia hal itu perlahan tergerus oleh konversi hutan dan eksploitasi perusahaan berskala besar di tanah-tanah adat. “Sekarang hutan mereka sudah diambil dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu. Obat-obatan sudah mulai hilang sehingga terpaksa ke puskesmas terdekat. Namun faktanya, perempuan adat lebih percaya dengan obat-obatan alami dan ini bikin kehidupan mereka jadi agak sulit,” kata Magdalena dalam konferensi pers di Kemang Selatan, Jakarta, Selasa (9/8).
Baca Juga :Film Taklukan Mimpi, Kenalkan Peradaban Papua
Dikatakan Magdalena, hilangnya akses pada tanah adat berdampak lebih besar kepada perempuan adat. Selain kehilangan sumber obat-obatan, perempuan juga mengalami dampak kerusakan lingkungan maupun ketidakadilan ekonomi. Hal ini membuat perempuan adat harus menambah tenaga dan waktu untuk usaha produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Ini terjadi karena perempuan memiliki keterkaitan erat dengan tanah, hutan dan lingkungan.
Seperti dikisahkan oleh Veronika Manimbu, warga Suku Mpur dari Kampung Arumi, Distrik Kebar Timur, Tambrauw, Papua Barat. Kata dia ekspansi perusahaan jagung di Lembah Kebar yang merangsek ke tanah ulayatnya memaksa Veronika untuk membuka ladang lebih jauh. “Kalau dulu jarak ladang kasbi (singkong, red) dan sayuran dari rumah hanya 100 meter saja. Sekarang harus jalan kaki ke ladang sekitar dua-tiga jam. Sangat jauh. Kita setengah mati berjalan, karena hutan kami sudah habis digusur perusahaan,” kata Veronika.
Baca Juga :Rumah Kopi Amungme Gold Semangati Petani Papua
Hal serupa dialami Rosita Tecuari, perempuan adat Namblong dari Kabupaten Jayapura. Deforestasi karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit juga seolah ‘memutus’ hubungannya dengan alam.
“Dulu setiap hari kami bisa dengar suara cenderawasih, kasuari… Tapi sekarang tidak ada lagi sejak hutan kami digusur sekitar 7 ribu hektare. Hari ini hutan kami gundul, dan kami perempuan merasa sedih. Hati kosong, karena cenderawasih itu seperti anak bagi kami,” keluh Rosita.
Sornica Ester Lily, peneliti Asia Justice and Rights (AJAR), mengatakan pola pembangunan dan perluasan industri ekstraktif di Tanah Papua masih manipulatif dan tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh. Masyarakat yang digandeng terbatas pada satu atau dua individu tertentu dan dibarengi dengan pemberian uang yang kemudian diklaim sebagai ‘tali kasih’ atau kompensasi.
“Selain itu kami menemukan adanya penyingkiran ruang perempuan dalam negosiasi adat (dalam hal masuknya perusahaan di tanah ulayat). Salah satu masalah utama selama ini adalah belum adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat. Dan Papua dianggap sebagai tanah kosong, padahal sudah ada yang punya. Karena itu pengakuan masyarakat adat menjadi penting dan harus menjadi fokus utama,” kata Sornica.